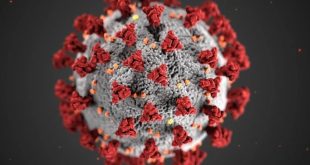Setiap tanggal 30 September bangsa kita memperingati peristiwa paling menggenaskan sekaligus memilukan. Di rentang 30 September hingga 1 Oktober 1965 tepatnya di Jakarta dan Yogyakarta terjadi peristiwa dimana enam perwira tinggi dan satu perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya disiksa secara kejam dan dibunuh dalam upaya kudeta dan pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Momen sejarah ini tak lekang oleh waktu terutama di ingatan para generasi 90 ke bawah. Karena generasi tersebut memperoleh porsi pengetahuan lebih banyak baik dari bangku sekolah hingga berbagai pagelaran dan media masa lalu.
Namun dalam kurun dekade belakangan pengetahuan terhadap peristiwa 30 September patut dipertanyakan.
Apakah tragedi berdarah yang dibumbui penghianatan terhadap bangsa tersebut diketahui oleh generasi milenial. Apalagi dewasa ini ada kecenderungan ketika mendekati hari peringatan peristiwa pemberontakan dan pengkhianatan yang akrab dikenal dengan singkatan G30S/PKI tersebut selalu saja muncul diskursus dan perdebatan tiada henti di ruang publik. Perdebatan yang dikhawatirkan bisa membuat jenuh generasi milenial serta berkemungkinan memunculkan persepsi dan anggapan di benak mereka bahwa fragmen penting sejarah pengkhianatan PKI seakan bagian dari drama dunia politik. Ketika sejarah sudah dipertanyakan tentu alarm bahaya bagi bangsa ke depan.
Perdebatan muncul disebabkan keinginan sejumlah pihak yang berupaya menolak dan mendiskreditkan penayangan mahakarya film yang coba merekam dan menceritakan peristiwa kelam tersebut. Karya film dimaksud tentu saja karya lawas yang selalu ditayangkan di saat 30 September sejak dulu melalui media televisi dan media lain semisal “layar tancap” yang disaksikan secara bersama-sama dalam lingkup komunitas.
Munculnya perdebatan di kala peringatan 30 September mengundang keheranan. Ada apa? Jika memang pihak menilai karya film yang selama ini telah disaksikan ratusan juta mata masyarakat Indonesia sejak dahulu itu belum secara objektif menggambarkan peristiwa, maka dalam konteks demokrasi sah-sah. Tapi harus disampaikan berdasarkan dengan data dan fakta bukan rasa. Namun yang terjadi selama ini justru bak lembar batu sembunyi tangan. Melempar opini ke publik lantas tidak bertanggungjawab. Toh film tersebut juga dibuat berangkat dari riset panjang dan didasarkan dari pengakuan banyak pihak yang terlibat baik langsung dan tidak langsung di masa duka tersebut.
Disamping rutinitas silang pendapat muncul setiap tahun peringatan G30S/PKI, terkait sejarah ada hal lain perlu diangkat. Karena boleh jadi bakal berimbas makin tereduksinya informasi mengenai peristiwa pengkhiatan 30 September. Apalagi kalau bukan mengemukanya wacana perubahan kebijakan terhadap mata pelajaran sejarah yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebagaimana tertuang dalam penyederhanaan kurikulum kabarnya berlaku Maret 2021 yang bahkan telah di sosialisasikan oleh Kemendikbud dalam agenda asesmen tingkat nasional, bahwa mata pelajaran sejarah Indonesia tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa SMA/sederajat kelas 10, melainkan digabung dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan sosial (IPS). Kebijakan ini tentu sama sekali berbeda. Dalam kurikulum 2013 dan selama ini mata pelajaran sejarah Indonesia bersifat wajib dipelajari dan terpisah dari mata pelajaran lainnya.
Maka tak heran kebijakan tersebut menuai kontroversi dan protes keras dari berbagai pihak terutama aktor dunia pendidikan. Salah satunya disampaikan ketua Umum PB PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd yang bahkan menyerukan ke semua insan PGRI se-Indonesia berjuang mempertahankan mata pelajaran sejarah agar tetap eksis dalam kurikulum nasional.
Bukan Nostalgia
Berkaca dari dua fenomena di atas, khususnya terakhir mengenai perubahan kebijakan terhadap ilmu sejarah, sepertinya ada kesan ingin merubah pandangan terhadap sejarah. Dari sejarah sebagai bahan evaluasi dan proyeksi di masa sekarang dan akan datang menjadi “kenangan”. Sehingga sejarah bak cerita nostalgia yang pahit, getir dan sedihnya tinggal di masa lalu; bahagia, senang, dan riang pun dilupakan seiring waktu berlalu.
Pandangan menganggap sejarah seperti nostalgia lantas hanya fokus terhadap masa sekarang dan akan datang, jelas kesalahan fatal. Memang ada perkataan orang tua “yang lalu biarkan berlalu, jangan biarkan masa lalu membelenggumu”. Ini benar, tapi lihat dulu apa harus dibuang. Jangan sampai kita membuang mutiara dan mengambil kerang. Sejarah adalah identitas manusia bangsa. Melalui sejarah, insan mengikat pola berpikir dan karakter.
Jerman terkenal sebagai negara industri karena sejarah masa lalu, Jepang dengan karakter dan etos kerjanya juga karena sejarahnya, begitujuga negara maju lainnya. Oleh karena itu membangun identitas sebuah keharusan. Tanpa identitas, kita tak ubahnya binatang yang berakal. Bagi suatu bangsa, menjaga identitas adalah kunci untuk mempertahankan eksistensinya dalam peradaban dunia.
Maka kembali ke kebijakan terkait pelajaran sejarah tadi, materi dan muatan seharusnya justru diperkuat dengan pendalaman dan pengayaan agar identitas tersebut tetap terjaga, bukannya dikurangi atau malah dihapus. Terutama memperkaya khazanah sejarah nasional dengan sejarah daerah/lokal yang punya motivasi sama dalam kerangka perjuangan nasional, meski kejadiannya saat itu bersifat lokal. Sejarah kerajaan Melayu di bumi Riau misalnya punya ruh perjuangan dan kontribusi besar dalam pentas nasional di masa penjajahan dan kemerdekaan. Termasuk ketika Sultan Syarif Kasim II menyerahkan mahkota, istana, dan hampir seluruh kekayaan Kesultanan Siak Sri Inderapura kepada pemerintah RI. Sumbangan dalam bentuk uang sebesar 13 juta gulden diberikan secara cuma-cuma oleh Sultan Syarif Kasim II kepada Presiden Sukarno tentu saja bukan jumlah yang kecil. Jika ditakar nominalnya kira-kira setara 69 juta euro atau lebih dari 1 triliun rupiah. Mengacu ke sejarah tadi agak aneh kenapa pemerintah pusat masih saja belum adil memperlakukan Riau.
Tidak hanya perjuangan, Riau juga punya sejarah pengkhianatan yang pernah terjadi di bumi Riau saat terjadi kekosongan kekuasaan ketika proklamasi 17 Agustus 1945. Di sejumlah wilayah yakni Pekanbaru, Selat Panjang dan Bagansiapi-Api (dikenal dengan “peristiwa bendera”) terjadi perlawanan dan penolakan terhadap kemerdekaan Indonesia*. Saat itu ada pihak yang menolak mengibarkan bendera merah putih dan malah mengibarkan bendera Koumintang sebagai tandingan, bendera yang dipakai di Cina, Taipei dan Taiwan dulunya. Sejumlah peristiwa sejarah dan banyak lainnya inilah yang mulai terlupakan atau seakan coba dilupakan. Peninggalan sejarahnya pun sudah banyak yang tak terawat.
Oleh karena itu, apresiasi terhadap sejarah di daerah bukan sekedar formalitas berupa pemberian gelar kepahlawanan terhadap tokoh daerah. Akan tetapi paling utama menjaga legacy dan esensi perjuangan para tokoh dan pejuang di masa lalu dapat terus lestari di benak generasi bangsa saat ini dan ke depan. Dan perlu juga menjadi catatan, mempelajari sejarah bukan berarti membangkitkan sentimen dan emosi di masa lalu dan menghadirkannya di masa sekarang. Ini pandangan keliru tentang sejarah. Sejarah pada dasarnya adalah pelajaran untuk kehidupan sekarang dan akan datang agar kesalahan di masa lalu jangan sampai terulang, dan mari bersama buktikan loyalitas terhadap bangsa melalui pengorbanan dan perbuatan. Inilah makna mempelajari sejarah. Sebagaimana dikutip dari filsuf asal Spanyol George Santanaya “Mereka yang tidak mempelajari sejarah maka akan dikutuk untuk mengulangi sejarah itu sendiri”.
H. SOFYAN SIROJ ABDUL WAHAB, LC, MM. ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU
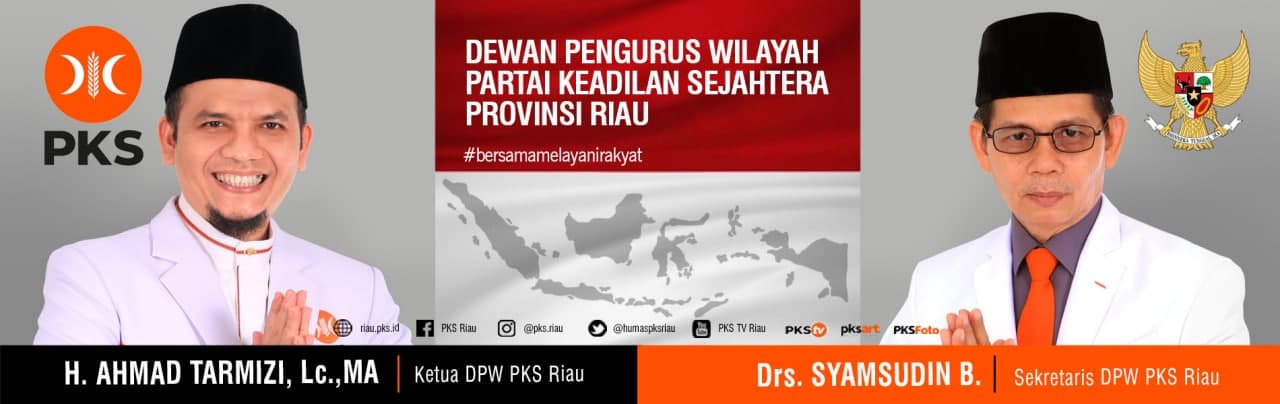 DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau