Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, tidak lepas dari perdebatan agar mencapai mufakat
Perumusan dasar-dasar negara atau seperti disebutkan Soekarno dalam bahasa Belanda “Philosofische grondslag” dilakukan dalam sidang BPUPKI. Tokoh Boedi Oetomo ditunjuk sebagai kaico atau ketua, yakni Radjiman Wediodiningrat. Sedangkan Raden Pandji Soeroso sebagai ketua mudanya.
BPUPKI beranggotakan 59 orang. Mereka terdiri dari berbagai golongan yang didominasi orang Indonesia, termasuk 4 orang dari golongan China, 1 orang golongan Arab, dan 1 keturunan Belanda.
Selain itu, ada pula tokubetu iin (anggota kehormatan), terdiri 8 orang Jepang. Namun mereka tidak punya hak bersuara seperti ditulis Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia VI (1984).
Tidak ada kelompak sekuler dalam pembahasan dasar Negara di sidang BPUPKI dan PPKI
Para founding father dalam BPUPKI tidak ada yang mempunyai sikap sekularisme memisahkan agama dan Negara dalam perdebatannya dalam menentukan dasar Negara. Sehingga bisa dikatakan ada dua kelompok besar pendapat yang berdebat pada saat itu,yaitu Islam-Nasionalis dan Nasionalis-religius.
Banyak dari kita anak bangsa saat sekarang ini tidak dapat memahami sejarah bahwa tidak ada kelompok sekular di dalam Sidang BPUPKI, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI). Hingga 1945, PKI masih dilarang (ilegal) oleh pemerintahan Jepang akibat pemberontakan pada 1926. Dengan ketiadaan anggota PKI dalam Sidang BPUPKI, otomatis tidak ada penganjur sekularisme dalam perumusan dasar negara. Mari kita telusuri jejak-jeja sejarah mengenai fakta ini dengan hati-hati sekali lagi.
Pancasila merupakan kesepakatan bersama antar elemen bangsa
Sidang BPUPKI digelar 2 kali. Pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni dan 10-17 Juli 1945.
Yang pertama mengutarakan rumusan asas dasar negara yakni M. Yamin. Ia memaparkan asas yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia nanti menurutnya sebanyak lima butir, yaitu, Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.
Lalu ide dasar negara juga muncul dari sosok Mr. Soepomo. Ia mengungkapkan rumusan serupa, yang diberi nama “Dasar Negara Indonesia Merdeka”, yaitu Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, serta Keadilan Sosial.
Kemudian di hari terakhir, Sukarno memperkenalkan 5 sila, yang terdiri dari Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sampai sidang tersebut selesai, keputusan belum mencapai mufakat. Menurut Bernhard Dahm dalam Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan (1987) ada beda pendapat yang cukup tajam antara kubu nasionalis dan kubu agamis mengenai pembentukan dasar negara itu.
Dibentuk Panitia Kecil BPUPKI
Oleh karena itu dibentuklah Panitia Sembilan atau panitia kecil dari BPUPKI sebagai cara untuk mencari jalan tengah. Mereka terdiri dari Sukarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, M. Yamin, Wahid Hasjim, Abdoel Kahar Moezakir, Abikusno Tjokrosoejoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis.
Hasil sidang Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 lahirlah rumusan dasar negara Indonesia yang dikenal sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang isinya:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Menurut Nannie Hudawati dkk dalam Risalah Sidang BPUPKI (1995) dalam proses mendirikan negara RI, memang terasa ada tarik menarik antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Di antara para anggota perumus dasar negara itu, mereka yang ingin mendirikan negara berdasarkan Islam yakni Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Sanusi.
Namun sikap Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Sanusi tidak saklek. Pada sidang kedua BPUPKI,14 dan 15 Juli 1945, mereka awalnya menyarankan agar agama Islam dijadikan dasar negara. Tapi karena sadar risiko terpecahnya negara bangsa jika usul itu dilaksanakan, maka keduanya mencabut kembali usulannya.
Perubahan sikap ini terjadi karena tidak jelasnya arti anak kalimat pada sila pertama Pancasila yakni “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Mereka kemudian meminta agar anak kalimat tersebut dicoret. Menurut mereka, jika BPUPKI tidak menyetujui negara berdasar agama maka negara bersikap netral saja terhadap masalah agama tersebut.
Ditambah lagi pada saat itu Hatta lalu melobi kelompok Islam. Hatta lewat Kasman Singodimedjo membujuk Ki Bagus agar rumusan Pancasila memakai kalimat seperti yang ada sekarang, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kesadaran akan peran penting religiusitas dan ketuhanan dalam dasar negara ini lalu ditandaskan oleh Soekarno. Dalam pidato 1 Juni 1945, ia menyatakan, “Saudara-saudara, apakah prinsip ke-5? Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan!” Selanjutnya ia menambahkan, “Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan… ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau Saudara-saudara menyetujui bahwa Indonesia Merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!” Tekanan ketuhanan sebagai dasar negara ini ia tegaskan melalui kalimat, “Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang bertuhan!”
Dengan demikian, ketuhanan menjadi kalimat bersama (kalimatun sawa’) antar-kelompok nasionalis-religius dengan Islam-nasionalis. Keduanya berbeda soal posisi Islam dalam dasar negara, namun satu kata soal keharusan ketuhanan sebagai bagian utama dari dasar negara. Ketika menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima, maksud Soekarno ialah menempatkannya sebagai “akar tunggang” Pancasila. Artinya, sila kebangsaan, kemanusiaan, musyawarah dan kesejahteraan sosial dibangun di atas akar ketuhanan.
Dalam kaitan ini, ketuhanan yang digagas Soekarno ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diamalkan secara beradab dan berbudaya. Sehingga maksud dari frasa “ketuhanan yang berkebudayaan”, ialah pengamalan dari iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertuhan secara kebudayaan artinya beragama secara beradab dan toleran. Menurut As’ad Said Ali dalam Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa (2009: 160), karena menggagas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sila dalam Pancasilanya, pidato Soekarno lalu diterima secara aklamasi sebagai bahan baku bagi perumusan dasar negara.
Mengapa? Karena sila ketuhanan ini melegakan dua kelompok. Kelompok Islam sepakat sebab di dalam dasar negara memuat ketuhanan yang merupakan cerminan dari tauhid. Demikian pula kelompok nasionalis menerima karena ketuhanan tersebut merupakan prinsip umum keagamaan yang tidak mewakili doktrin agama tertentu.
Piagam Jakarta
Visi ketuhanan baik dari kelompok Islam maupun nasionalis ini berjalin kelindan dengan spirit kebangsaan. Inilah yang membuat tokoh-tokoh Islam bersedia mencoret tujuh kata “dengan kewajiban menjalan syariat Islam bagi pemeluknya” dalam Piagam Jakarta, karena pertimbangan persatuan nasional. Pagi hari menjelang Sidang PPKI, 18 Agustus 1945, Bung Hatta melobi Ki Bagus Hadikoesoemo, Kiai Wahid Hasyim, Kasman Singedimedjo dan Teuku Hasan. Tokoh-tokoh Islam ini sepakat mengganti “tujuh kata” dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mengutamakan persatuan, apalagi kemerdekaan bangsa sedang di bawah ancaman Sekutu.
Spirit kebangsaan ini juga dikembangkan oleh Soekarno. Banyak orang tidak mengetahui, bahwa Soekarno bersikukuh dengan “tujuh kata” tersebut demi terjaganya persatuan. Ketika perdebatan tentang “tujuh kata” ini mengalami kebuntuan, pada Sidang Kedua BPUPKI, 16 Juli, dengan berlinang air mata ia menghimbau kelompok nasionalis agar menerima Piagam Jakarta demi tercapainya kesepakatan tentang dasar negara (Yudi Latif, 2011: 81). Konsen Soekarno terhadap aspirasi Islam ini ia lanjutkan dengan menempatkan Piagam Jakarta sebagai nilai yang menjiwai UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959.
Dengan demikian, jika saat ini terdapat tuduhan sekularisasi terhadap Pancasila, atau Soekarno; maka tuduhan tersebut tidak berpijak pada fakta sejarah yang tepat. Kita harus belajar dari para perumus Pancasila yang mengimani ketuhanan pada satu sisi, namun tetap membangun nasionalisme pada saat bersamaan. Tidak ada paradigma sekular di dalam Pancasila, karena tokoh-tokoh Islampun selalu mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Dalam konteks inilah, perdebatan terkini tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) selayaknya tidak membangkitkan konflik ideologi antar-anak bangsa. Sebab konflik tersebut sebenarnya berangkat dari pemahaman semu atas hubungan Pancasila, ketuhanan dan Islam. Semua pihak harus kembali pada spirit awal pendiri bangsa yang mengutamakan persatuan di atas perbedaan.
Salam total leadership !!
Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM
(Anggota DPRD Provinsi Riau)
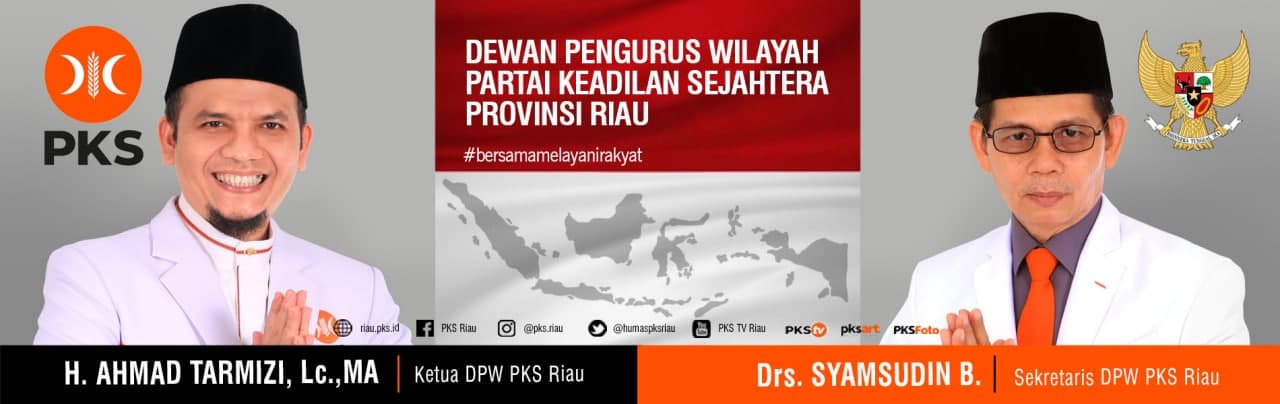 DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau






