 Ada hal cukup mengejutkan datang dari lisan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar saat pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Gedung Daerah Balai Serindit pada Senin (12/4/2021). Orang nomor satu di Riau menyinggung permasalahan lahan kebun sawit. Disampaikan bahwa dari 3,4 juta Hektare (Ha), baru 9 ribu Ha yang punya izinHak Guna Usaha (HGU) adapun sisanya 1 juta Ha lebih belum HGU. Kemudian 1,2 juta Ha statusnya ilegal atau berada di kawasan hutan. Dalam pernyataannya, Gubri juga menyinggung peran mafia tanah yang bikin sengkarut masalah pemanfaatan lahan di bumi lancang kuning. Dalam kesempatan tersebut pula Gubri meminta Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI untuk segera menurunkan tim inventarisasi kebun sawit di Provinsi Riau.
Ada hal cukup mengejutkan datang dari lisan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar saat pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Gedung Daerah Balai Serindit pada Senin (12/4/2021). Orang nomor satu di Riau menyinggung permasalahan lahan kebun sawit. Disampaikan bahwa dari 3,4 juta Hektare (Ha), baru 9 ribu Ha yang punya izinHak Guna Usaha (HGU) adapun sisanya 1 juta Ha lebih belum HGU. Kemudian 1,2 juta Ha statusnya ilegal atau berada di kawasan hutan. Dalam pernyataannya, Gubri juga menyinggung peran mafia tanah yang bikin sengkarut masalah pemanfaatan lahan di bumi lancang kuning. Dalam kesempatan tersebut pula Gubri meminta Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI untuk segera menurunkan tim inventarisasi kebun sawit di Provinsi Riau.
Apa yang disampaikan Gubri sebenarnya persoalan klasik. Namun perlu terus disuarakan. Apalagi paska berlakunya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang menurut janji manis Pemerintah saat pembahasan, beleid tersebut akan memfasilitasi penyelesaian kebun sawit yang berada di kawasan hutan. Saat ini peraturan implementasi UU Ciptaker baik itu PP maupun Permen memang belum jelas. Tapi diharapkan janji Pemerintah dapat dibuktikan dan benar-benar mengakomodir kebutuhan daerah, terutama Pemda yang ingin solusi konkrit atas konflik lahan. Terkait HGU menyebabkan kesenjangan antara pemilik kebun sawit yang mayoritas dimiliki pengusaha besar dengan masyarakat tempatan pada akhirnya memicu perseteruan dan konflik berkepanjangan. Maka sudah tepat concern Gubri terhadap aturan pelaksana nantinya supaya bagi pengusaha dengan kepemilihan lahan 100 Ha atau perusahaan yang belum memiliki legal (izin) agar memberi masyarakat setempat minimal 20 persen sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan.
Amanah Konstitusi
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” begitu kutipan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3. Hampir semua kita hafal. Namun implementasinya kian hari kian sulit didapati. Lahan sebagai akses perekonomian paling murah dan mudah dicapai tetapi kenyataannya masyarakat adat dan tempatan makin terasing dan sulit bertahan hidup di atas lahan yang telah didiami secara bergenerasi. Mirisnya, tak sedikit pemilik lahan besar mengangkangi aturan dengan merambah kawasan hutan. Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata saat berkunjung ke Riau pada 2019 membeberkan fakta, dari 1 juta Ha kebun sawit yang mengokupasi areal hutan paling besar dikuasai perusahaan tanpa izin. Untuk Riau, perambahan areal hutan bahkan pernah melibatkan BUMN. Berikut ada juga perusahaan perkebunan tak punya NPWP alias tak bayar pajak. Temuan-temuan tadi terangkum dalam laporan Pansus Monitoring Lahan yang dibentuk DPRD Provinsi Riau periode lalu.
Gubri juga mengungkap fakta miris lain banyaknya HGU tanpa Plasma. Mengingat kompleksnya masalah memberi ancaman nyata terhadap masa depan Riau, maka perlu ada langkah strategis menyikapinya. Karena selain merugikan masyarakat Riau yang mayoritas menggantungkan hidup dari sektor perkebunan dan pertanian sebagai sumber perekonomian, juga merugikan Pemda sebagai sumber pendapatan daerah. Apalagi UU Ciptaker mengizinkan perpanjangan HGU menjadi 90 tahun, yang bikin aturan tersebut jauh lebih “hebat” dari masa penjajahan (di masa kolonial hak serupa dikenal dengan erfpacht, memperbolehkan pengusaha mengelola tanah hingga 75 tahun). Panjangnya masa pengelolaan harusnya dibarengi persyaratan dan pengawasan ketat agar tidak ada peraturan yang dikangkangi serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan di daerah. Jika tidak, ke depan kesenjangan makin melebar dan potensi eskalasi konflik sulit diredam.
Tak Sepadan
Pemda tentu dalam posisi dilematis. Bagi daerah pendapatan dari pengurusan izin lahan memang bisa miliaran rupiah masuk ke kas daerah. Namun, pemasukan tersebut tentu butuh waktu untuk menanti sampai perpanjangan izin baru.
Apesnya anggaran daerah banyak terpakai untuk membangun dan memperbaiki jalan rusak akibat kendaraan bertonase besar yang didominasi truk pengangkut sawit namun tak sepadan dengan keuntungan diperoleh daerah. Pemilik kebun dan perusahaan perkebunan sebagian besar juga dimiliki orang luar daerah. Kantor pusatnya pun di provinsi lain hingga luar negeri. Paling menderita masyarakat, baik itu akibat kelalaian pemanfaatan lahan dan kerusakan jalan. Jadi wajar provinsi sentra sawit minta perhatian lebih dari Pemerintah Pusat, termasuk memperoleh ekstensifikasi pendapatan. Semisal Pemda Aceh pernah mencoba menambah PAD dari sektor perkebunan sawit swasta melalui Perda mengenakan retribusi Rp. 5/Kg tandan buah yang dihasilkan perusahaan. Sayangnya Pemerintah Pusat membatalkan karena dianggap tidak ramah investasi.
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan, besarnya ketergantungan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat Riau dari sektor perkebunan harus disertai solusi bijak dan bersifat jangka panjang sehingga tidak memperparah kesenjangan. Pertama, terkait HGU Menteri LHK Siti Nurbaya memang menyebut UU Cipta Kerja masih mewajibkan perusahaan sawit membangun plasma sebesar 20% dari luas konsesi. Namun penerapannya harus dikawal dan diawasi ketat supaya hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan konservasi dan hal yang mendorong penanganan konflik tenurial dapat dipenuhi secara mutlak. Tanggung jawab jelas tak hanya di pundak pemerintah pusat namun juga jajaran pemerintah di daerah. Kedua, keterbukaan informasi dipandang sebagai salah satu solusi dan perlu dimiliki pihak/instansi berwenang. Terkait lahan, keputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau yang menyebut dokumen HGU perkebunan sawit di Riau tergolong informasi publik dan bersifat terbuka patut diapresiasi. Karena masyarakat juga perlu mengetahui HGU perusahaan, paling ketara sebagai panduan mengidentifikasi sempadan tanah yang berbatasan sebagai acuan legalitas tanah dan keperluan lain. Disamping pendekatan tadi tentu banyak cara lain. Intinya kita ingin pemanfaatan lahan dan tanah sebagai interpretasi dari kata “bumi” dalam UUD 1945 berangkat dari hak dan kewajiban sama dari perusahaan dan pemilik modal juga masyarakat adat dan tempatan. HGU pada prinsipnya bagus sebagai formasi modal nasional bertujuan memperoleh keuntungan dari investasi dengan tetap berorientasi memberi keuntungan bagi rakyat. Masalah muncul ketika pemodal lebih diuntungkan sementara rakyat dibuntungkan.
H. SOFYAN SIROJ ABDUL WAHAB, LC, MM. ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU
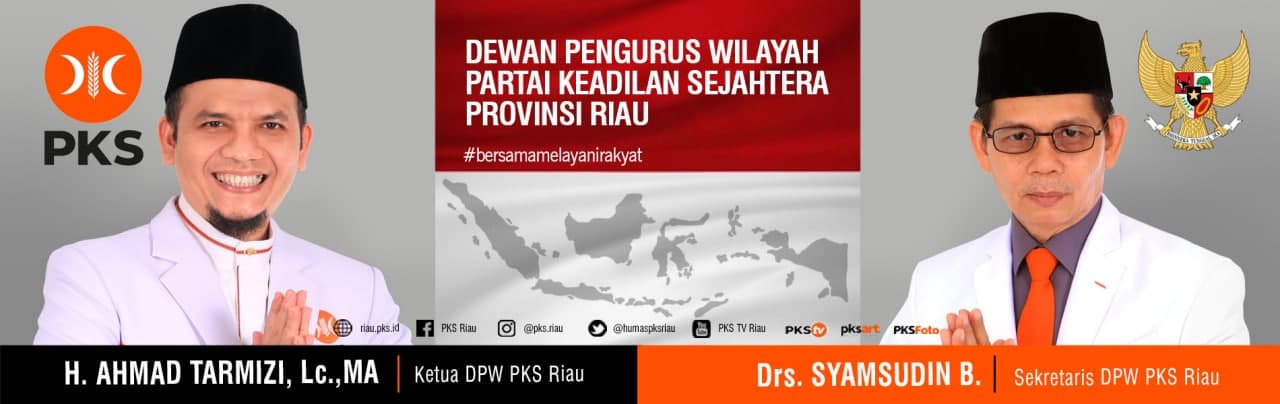 DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau




