
Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap: merdeka atau mati!
Dan kita yakin saudara-saudara,
Pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara. Tuhan akan melindungi kita sekalian.
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Kalimat di atas sepenggal pidato lantang Bung Tomo yang menggugah dan membakar semangat jelang pecah pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, yang disampaikan melalui Radio Pemberontakan milik Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) di Surabaya. Sekedar kilas balik, 10 November 1945 bukan kejadian tunggal. Bermula 25 Oktober 1945, perwira angkatan darat India-Inggris Mallaby dan serdadunya mendarat di Tanjung Perak dengan misi melucuti senjata pasukan Jepang. Selain itu tersebar ancaman yang memerintahkan laskar rakyat Surabaya menyerahkan senjata ke sekutu dalam waktu 2 hari. Tentu saja memantik amarah rakyat Surabaya. Tak berselang lama, pos sekutu di wilayah Surabaya diserbu. Mallaby yang terdesak lalu meminta para pemimpin republik yaitu Soekarno, Hatta dan Amir Sjariffudin datang ke Surabaya untuk bikin kesepakatan penghentian serangan terhadap tentara Sekutu. Tapi situasi tak kunjung mereda. 7 November sekutu mengultimatum Gubernur Jawa Timur (Jatim) bahwa akan menduduki Surabaya jika tak mampu kendalikan keadaan. Berikut menekan pemimpin republik, komandan laskar dan seluruh pemuda bersenjata agar menyerah selambatnya pukul 6 sore hari yang sama. Puncaknya, 10 November Gubernur Jatim melalui radio menolak ultimatum yang memicu peristiwa bersejarah dan peperangan terbesar paska kemerdekaan.
Meski secara kekuatan para pejuang kalah telak dari sekutu, satu hal yang tak bisa disangkal bangsa ini keluar dari medan pertempuran dengan kepala tegak. Berani mempertahankan kemerdekaan walau harus berkorban nyawa. Dalam mengenang momen historis, sudah sepantasnya generasi bangsa tak lupa akan sejarah dan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Refleksi dan kontemplasi inilah yang diharapkan mengisi peringatan hari pahlawan. Bukan malah disibukkan dengan narasi mencari pahlawan masa kini, yang justru akan mengurangi khidmat dan hikmah hari pahlawan. Karena perjuangan para pendahulu tak tergantikan dan bisa dibanding-bandingkan. Bicara refleksi, banyak I’tibar yang bisa kita peroleh dan bernilai manfaat bagi perjalanan bangsa di masa kini dan kepentingan masa mendatang. Adapun dalam kesempatan kali ini, satu hal yang perlu ditelaah dari kejadian 10 November 1945 adalah menggali apa yang memotivasi para pejuang berani berkorban meski secara angka dan persenjataan jauh di bawah sekutu penjajah?
KUNCI
Kalau kita tarik kesimpulan dini kuncinya satu: karakter. Pribadi berkarakter kokoh dan kuat berupaya menegakkan kebenaran dalam keadaan apapun. Sifat ini jelas tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat. Butuh proses penempaan dan tekad kuat. Kisah Bung Tomo paling pas diangkat. Selaku pengobar semangat tempur dalam Peristiwa 10 November 1945, ia bukan pria cepak sebagaimana ciri khas tentara dan bukan lulusan akademi militer. Namun berani bersuara menentang penjajah. Bung Tomo pendiri dan pemimpin laskar yang beranggotakan hingga luar pulau Jawa, membuat dia ditarik ke Kementerian Pertahanan. Ia bukan satu-satunya tokoh menonjol saat itu. Di antara sekian perwira penting dalam palagan 10 November 1945, banyak punya pengalaman di bidang militer seperti Jenderal Mayor Mohammad Mangunprodjo, Kolonel Sungkono, Kolonel Djonosewojo hingga Kolonel Moestopo. Kendati begitu, Bung Tomo kesohor dan disegani. Lewat pidatonya yang lazim diawali dengan kalimah “Bismillahirahmanirahim” dan diakhiri pekik “Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka!”, sukses memacu andrenalin para pejuang. Bung Tomo menepis opini sesat yang kerap mendiskreditkan ajaran Islam seolah sumber perpecahan. Juga mereka yang berkata bahwa membawa agama dalam urusan publik memecah belah bangsa. Pidato Bung Tomo justru berhasil mempersatukan. Ia pernah berujar “Andai tak ada takbir, saya tidak tahu dengan cara apa membakar semangat para pemuda melawan penjajah”. Bung Tomo menyebut “Pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi” sebelum menyebutkan daerah lain.
Di sini pelajaran berharga. Dulu tokoh menyuarakan narasi untuk kepentingan bangsa. Sementara sekarang, simbol dan filosofi negara seperti Pancasila dijadikan tameng guna melindungi kepentingan kelompok dan menyerang pihak berseberangan dengan tuduhan menebar kebencian, radikal, anti Pancasila dan anti NKRI. Jadi, politik identitas termasuk agama bukan sumber persoalan di negeri ini. Bencana bagi bangsa manakala kebenaran dimanipulasi biar tampak salah dan segala cara dipakai untuk memoles kezaliman biar tampak benar. Kisah Bung Tomo juga mengandung nilai pentingnya konsistensi menyuarakan kebenaran dalam bingkai amar ma’ruf nahi mungkar. Kembali ke sejarah, paska peristiwa 10 November 1945 laskar-laskar banyak dilebur masuk TNI. Kala itu Panglima Besar dijabat Soedirman dan Menteri Pertahanan dipegang Amir Sjarifuddin yang dikenal sebagai tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Hubungan Amir Sjarifuddin dengan Bung Tomo boleh dibilang kurang akur. Menurut cerita istrinya di buku berjudul “Bung Tomo Suamiku”, ketika tiba di Tawangmangu (meninjau RRI), Bung Tomo mendapat pemberitahuan lewat telegram dari Menteri Pertahanan. Bung Tomo diminta memilih: tetap menjadi jenderal namun tak boleh berpidato atau berhenti jadi jenderal tetapi bisa berpidato. “Aku melihat Mas Tom Merenung, lalu tiba-tiba ia membalikan badan dan dengan nada marah berkata: ‘Persetan, ora dadi jenderal ya ora patheken,’” ujar istrinya. Sikap barusan menggambarkan betapa jabatan tak membuat konsistensi Bung Tomo menyuarakan kebenaran surut. Ya, Bung Tomo termasuk anti-PKI dan tergolong kritis terhadap Presiden Sukarno di masa Orde Lama. Sikap sama berlanjut sampai era Orde Baru.
Kokohnya sosok Bung Tomo tak bisa dipisahkan dari kedekatan dengan para kiai dan dunia santri. Pergolakan 10 November 1945 juga bukti besarnya pengaruh agama menyadarkan para pejuang terdahulu untuk hidup bermartabat dan memerangi unsur-unsur yang dapat menghinakan manusia. Peristiwa tersebut buah dari Resolusi Jihad yang dikumandangkan oleh para kiai pada tanggal 22 Oktober 1945. Diantara poin dalam resolusi dimaksud menyatakan “Berperang menolak dan melawan penjajah itu fardlu ‘ain (harus dikerjakan tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersendjata atau tidak) bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi fardlu kifayah (yang cukup, kalau dikerjakan sebagian saja)…” Keputusan tadi serta merta disyiarkan ke seluruh masjid hingga langgar di Surabaya dan sekitarnya. Namun, Resolusi Jihad rupanya menggema ke seluruh pelosok Jawa hingga Sumatera. Usai Resolusi Jihad bergaung, gerakan perlawanan kaum santri terhadap pasukan-pasukan sekutu semakin gencar di di pedesaan sampai kota-kota besar. Berbagai front pertempuran ikut turun termasuk laskar pejuang legendaris lainnya yaitu Hizbullah. Berangkat dari pemaparan, tergambar urgensi pelajaran sejarah untuk mengenali unsur-unsur yang membangun karakter bangsa. Sangat disayangkan tahun 2020 sempat muncul isu pelajaran sejarah akan digeser dari mata pelajaran wajib SMA sederajat dalam kebijakan penyederhanaan kurikulum yang digodok Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Meski tak jadi, narasi menggeser pelajaran sejarah terlanjur ditafsirkan sekedar uji ombak: kalau tidak mendapat protes keras boleh jadi terwujud. Seharusnya pelajaran sejarah diperkuat. Karena melalui pembelajaran sejarah kita tahu modal utama yang mengantarkan bangsa meraih kemerdekaan, yakni pentingnya pendidikan jiwa dan karakter.
H. SOFYAN SIROJ ABDUL WAHAB, LC, MM. ANGGOTA KOMISI V DPRD PROVINSI RIAU
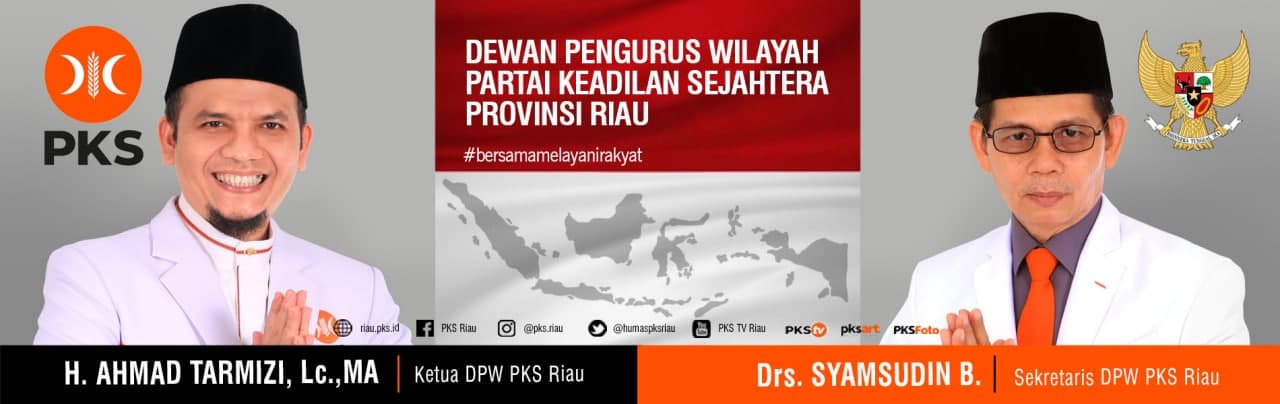 DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau





